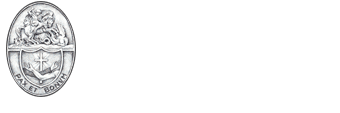By. Eddy Kristiyanto OFM
Ada anggapan bahwa menjadi orang beragama itu sangat sering berarti dangkal, dianggap mencari gampangnya, tidak mau bersusah-susah, bodoh, picik, tidak mau berpikir, fanatik, percaya buta, berlindung dengan ajaran soleh (kata-kata ulama, santo-santa, imam, gereja, tradisi), puas, takdir, kuwalat, dan sebagainya, dan sebagainya….. Semua itu diasalkan pada atau berujung pada mukjizat, kepercayaan pada Tuhan yang melampaui segala apa.
Dalam masa lalu, kepercayaan pada takhayul, kepercayaan sia-sia, gugon-tuhon, hal-hal goib, kutuk-mengutuk, otoritas begitu kuat, sampai menutup mata terhadap akal budi (pemikiran kritis) menimbulkan perlawanan dan sampai-sampai memunculkan arus anti-agama, ateisme, bahkan anti-klerikalisme.
Kita memperoleh asupan bermakna melalui bacaan teks yang berbicara tentang tanda-tanda dan mukjizat (baca: Kisah para Rasul 20:19-23). Juga teks-teks Kitab Suci dalam Oktaf Paskah pun berbicara tentang tanda-tanda yang tidak masuk nalar, tidak mudah dicerna oleh nalar telanjang, dibumbui dengan ketidakpercayaan, dan utamanya yang berfokus pada kebangkitan. Sebagaimana teks yang kita baca: kisah tentang Didimus (Tomas) yang terkenal itu (baca: Injil Minggu Kerahiman Ilahi).
Pengalaman, sekalipun sangat penting dan perlu, selalu terbatas. Sejarah pemikiran empirisme dan positivisme seperti yang diangkat da diproklamasikan oleh David Hume dianggap rapuh dan lemah. Tetapi dengan rasionalisme yang disulut René Descartes yang mau mengatasi kecupetan empirisme juga menampilkan kepincangan dan kecingkrangan.
Dengan demikian tidak ada jalan-yang-satu-sungguh-mengatasi-yang-lain, dan sebaliknya. Semua jalan ada kelemahan, di samping kekuatannya. Mengeksklusikan satu jalan dengan mengesampingkan yang lain sama-sama mata gelap: gelap dalam pengalaman, gelap pula dalam nalar. Jadi, selalu terbatas, meski semua tidak Bahagia dan berikhtiar untuk keluar-dari-kesumpekkan. Sesungguhnya, inilah kondisi manusia apa pun pilihannya.
Kita tak mau cepat-cepat dengan memeluk “suatu keyakinan” yang melampaui segala-galanya, tanpa masuk dalam proses pencarian, dinamika
Kata-kata kunci yang kiranya mencerahkan adalah insan perlu terus-menerus mencari entah sampai kapan, di mana, dan akhirnya mengakui. Meminjam ungkapan St. Augustinus, Hatiku selalu gelisah, dan baru tenang kembali ketika beristirahat dalam Diri-Mu, ya Allah. (bdk. Confessiones, Lib 1,1-2,2.5,5).
Jadi, orang beragama perlu terus-menerus berjalan untuk mencari di kedalaman hati dan di ketinggian budi. Nirlelah. “Rasa” dahaga dalam pencarian itu mungkin dalam dapat dipuaskan melalui firman-Nya: Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. (Yohanes 20:29) *****